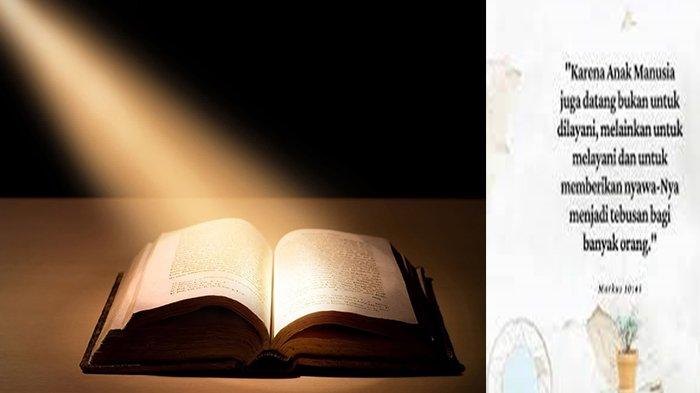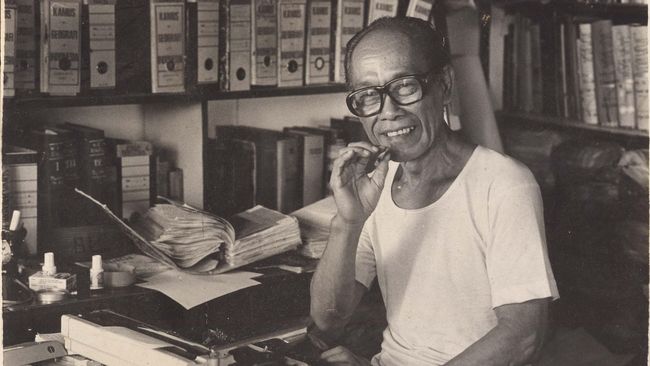Dering alarm memecah keheningan dini hari, angka digital merah menyala: pukul tiga pagi.
Seorang ibu terjaga, bangkit dari peraduannya. Langkahnya ringan menuju kamar mandi, air
wudhu membasuh sisa kantuk. Dengan gerakan yang sudah begitu akrab, ia berjalan menuju
kamarnya lalu menyalakan lampu.
“Pak..”.
Suaminya langsung membuka mata. Tanpa banyak kata, ia bangkit, mengambil wudhu, dan
bersiap menjalankan tahajud, seolah mereka sudah memahami tugas masing-masing. Salat
tahajud tak pernah terlewat, sebagai bentuk ikhtiar mereka untuk anaknya yang jauh di
perantauan. Doa-doa berhamburan ke langit malam, menggema dalam kesunyian rumah.
Di belahan dunia lain, di negeri dengan waktu yang merentang lebih panjang dari tanah air,
pagi telah berjalan lebih lambat. Matahari sudah meninggi, menandakan hari yang terus
beranjak. Di dalam sebuah rumah, Aisyah tengah bertukar argumen dengan teman
serumahnya. Udara di dalam rumah terasa lebih berat, seolah terisi penuh oleh ketegangan
yang tak tersuarakan. Piring kotor menumpuk di bak cuci, lantai berdebu, dan sampah yang
seharusnya ia buang sejak kemarin masih berserakan.
“Aku udah bilang besok pagi, kan? Kenapa sih ribet banget?” ujarnya kesal.
“Besok pagi? Udah dari 3 hari yang lalu kamu bilang gitu, Syah. Kita juga sibuk, tapi tetap
bagi tugas!” balas temannya.
Wajah temannya memerah, antara kesal dan lelah menghadapi alasan yang terus-menerus ia
berikan. Aisyah menghembuskan napas panjang, tak ada lagi ruang untuk kompromi. Tanpa
bicara lagi, ia mengambil tasnya, melangkah dan pergi, menenggelamkan diri dalam tugas-tugas yang menumpuk.
Langit mulai kehilangan warna, senja merangkak perlahan, meninggalkan jejak jingga yang
samar. Di sudut sebuah kafe kecil, Aisyah duduk terpaku. Di hadapannya, layar laptop
berpendar dingin, tumpukan kertas berserakan, dan secangkir kopi yang sudah dingin sejak
entah kapan. Ia mengetik, menghapus, lalu mengetik lagi. Pikirannya terlalu kusut untuk
menemukan solusi. Tugas kuliah menekan, tanggung jawab organisasi menjerat, dan suara
temannya yang penuh kekecewaan tadi masih terngiang di telinganya. Semesta seakan
menjadikannya sebatang kara di tengah keramaian.
Dering telepon menggema, mengiris keheningan. Nama “Ibu” tertera di layar. Sejenak, ia
membiarkannya bergetar, sebelum akhirnya menghela napas panjang dan menyerah.”Nak, firasat Ibu nggak enak. Jangan pulang malam, ya? Itu nggak baik. Dan sholat, Qur’an-nya jangan ditinggal.”
Suaranya lembut, seperti bisikan angin yang menerpa jendela. Ada getaran yang familiar di
sana, sesuatu yang dulu begitu menenangkan. Aisyah memejamkan mata, merasakan lelah
yang menggumpal di dadanya. “Iya, Bu,” jawabnya di akhir, singkat, nyaris tak terdengar.
Bukan karena enggan, tapi karena terlalu banyak perasaan yang ingin ia tahan.
Malam menjelma lebih pekat ketika Aisyah akhirnya membereskan barang-barangnya.
Tangannya gemetar kelelahan, tubuhnya seakan menjerit minta istirahat. Namun masih ada
pekerjaan, masih ada kewajiban yang tak bisa ia tinggalkan begitu saja. Hingga akhirnya, ia
menyerah. Jaket ia rapatkan, langkahnya menjejak trotoar yang dingin.
Jalanan yang biasanya masih menyimpan sisa kehidupan, malam ini terasa lebih sunyi.
Lampu-lampu jalan berdiri dalam diam, memancarkan cahaya redup yang seolah enggan
menyentuh tanah. Angin dingin menyusup di antara celah pakaiannya, membawa serta rasa
gelisah yang tak beralasan. Langkahnya semakin cepat, hatinya berdesir tanpa sebab.
Sebuah bayangan melintas di sudut matanya. Jantungnya berdegup kencang. Nafasnya
memburu. Dengan sisa keberanian yang ia punya, ia menoleh ke belakang, kosong. Tidak ada
siapa-siapa. Tapi ketakutan sudah mencengkeram dirinya. Ia mulai berlari, hampir tersandung
beberapa kali, sampai akhirnya tiba di tikungan gang sempit, waktu seolah membeku. Sebuah
tangan kasar mencengkeram pergelangan tangannya, menariknya ke bayang-bayang gelap.
Jantungnya berdegup liar, seperti burung kecil yang terjebak dalam genggaman pemangsa.
Sosok lelaki dengan tatapan kelam berdiri di hadapannya, napasnya berat, niatnya terselubung dalam kegelapan malam.
Aisyah ingin berteriak, namun suaranya tercekat. Ia ingin melawan, namun tubuhnya seakan
lumpuh. Dalam ketakutan yang membelenggu, pesan ibunya kembali terngiang, mengalun
dalam sanubarinya yang terhimpit kepanikan.
“Pertolongan Allah itu dekat…”
Dalam sisa kesadarannya, bibirnya bergetar melafalkan doa. Hatinya bergetar, menyeru satu-satunya nama yang mampu menolongnya. Dan seolah menjawab bisikannya yang lirih, suara
batuk seorang lelaki tua pecah di ujung gang. Bayang-bayang jahat itu tersentak,
cengkeramannya melonggar. Dalam sekejap, naluri Aisyah mengambil alih. Ia berlari
sekencang mungkin, napasnya tersengal, jantungnya berdegup begitu keras hingga ia merasa
dadanya akan meledak.
Pintu rumah terbuka dengan dentuman keras. Teman-temannya berhamburan keluar,
terkejut melihat Aisyah berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. Air
mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya luruh, membasahi pipinya yang dingin.Barang-barang di depannya berserakan, terhempas oleh tangannya yang gemetar—sebuah
isyarat betapa hatinya hancur. Ia yang selalu menjaga dirinya dengan baik, kini harus
menghadapi kenyataan pahit: disentuh dan hampir dilecehkan oleh pria asing yang entah darimana datangnya.
Isakannya memecah kesunyian malam, membawa serta ketakutan dan kelelahan yang selama
ini ia pendam seorang diri. Teman-temannya segera mendekat, berusaha menenangkannya.
“Syah… istighfar, Syah…” bisik seseorang dengan suara lirih.
Salah satu dari mereka menyodorkan segelas air putih, sementara yang lain memeluknya erat.
Malam yang panjang itu mereka lalui bersama, mencoba menguatkan Aisyah dalam luka yang tak terucapkan.
Hari-hari setelah kejadian itu terasa seperti menapaki hamparan kaca yang rapuh, setiap
langkahnya dipenuhi ketakutan akan pecahnya kepingan-kepingan luka yang masih segar.
Bayangan malam kelam itu terus menghantuinya—bersembunyi di balik kelopak matanya
yang lelah, menyelinap dalam sunyi, mengendap di sudut pikirannya tanpa ampun. Namun,
lebih dari sekadar trauma yang mencengkeramnya erat, ada sesuatu yang jauh lebih
menyakitkan: kesadaran bahwa ia telah melangkah terlalu jauh. Jauh dari doa yang dulu selalu
mengalir di bibirnya, jauh dari ketenangan yang dulu ia genggam erat, jauh dari cahaya yang
dulu membimbing setiap langkahnya dengan penuh kehangatan.
Dengan tangan gemetar, ia meraih ponselnya. Jemarinya ragu-ragu di atas layar sebelum
akhirnya menekan nomor yang sudah dihafalnya sejak kecil. Dering pertama, kedua—lalu
suara yang begitu akrab di telinganya menyapa dengan lembut.
“Bu…” suaranya tercekat, nyaris tenggelam dalam gelombang emosi yang membanjiri
dadanya. “Maaf… Aisyah salah. Doakan Aisyah, Bu… Aisyah nggak mau jauh dari Allah
lagi…”
Di seberang sana, terdengar keheningan sesaat. Seolah ibunya tengah mengumpulkan setiap
keping rasa yang ingin disampaikan. Lalu, dengan napas panjang, suara penuh keteduhan itu
hadir seperti pelukan yang tak terlihat, membalut luka yang selama ini menganga.
“Nak,” ucapnya pelan, namun penuh makna. “Allah tidak pernah jauh. Kita saja yang sering
lupa mencari-Nya.”
Sejenak, hanya isakan tertahan yang terdengar. Cahaya lampu kamar yang temaram
memantulkan bayangan wajahnya yang lelah di cermin. Namun, untuk pertama kalinya
setelah sekian lama, ia merasakan sesuatu yang telah lama hilang sebuah kehangatan yang
menyelusup perlahan, seperti embusan angin sejuk yang menenangkan jiwanya yang letih.